Dosa Sekolah pada Membaca
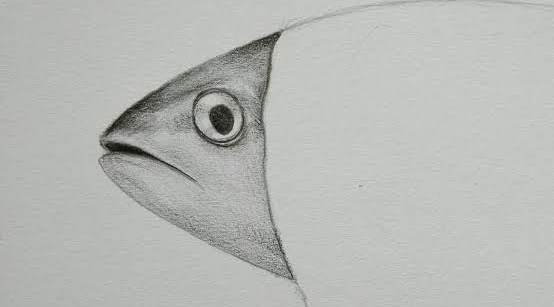
Ketika angka menjadi tujuan, membaca menjadi beban.
Oleh Benny Arnas
Pagi itu ruang kelas hening. Seorang siswa menunduk, menatap lembar ujian dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena ia tidak belajar, tetapi karena ia lupa satu rumus yang semalam dihafalnya. Di kepalanya tidak ada pertanyaan tentang makna soal itu. Yang ada hanya ketakutan pada satu hal: angka.
Di banyak sekolah, momen seperti ini bukan pengecualian. Ia adalah rutinitas. Sekolah telah menjadikan ujian sebagai pusat semesta. Nilai menjadi matahari, sementara proses berpikir hanya satelit kecil yang nyaris tak terlihat.
Sejak dini, siswa diajari bahwa belajar berarti mengumpulkan angka. Angka menentukan peringkat. Peringkat menentukan harga diri. Di titik ini, membaca, berpikir, dan bertanya tidak lagi bernilai kecuali jika berujung pada jawaban yang benar.
Sekolah perlahan bergeser dari ruang pencarian makna menjadi arena seleksi. Yang diuji bukan ketajaman nalar, melainkan kecepatan mengingat. Yang dihargai bukan pertanyaan, tetapi ketepatan memilih opsi A, B, C, atau D.
Dalam sistem seperti ini, membaca kehilangan martabatnya. Membaca tidak lagi menjadi kegiatan memahami, melainkan alat untuk menemukan jawaban tercepat. Buku dibaca dengan satu tujuan: keluar di ujian.
Penelitian tentang dampak ujian standar menunjukkan masalah serius ini. TeachHub mencatat bahwa standardized tests fail to test student’s ability to problem solve or think critically. Tes semacam ini lebih mengukur kemampuan mengingat jangka pendek daripada pemahaman konseptual yang mendalam.
Ketika hasil tes dijadikan tujuan utama, proses belajar mengalami distorsi. Donald T. Campbell menjelaskan fenomena ini melalui apa yang dikenal sebagai Campbell’s law. Ia menulis bahwa ketika skor tes menjadi tujuan pengajaran, maka tes tersebut kehilangan nilai diagnostiknya dan justru merusak proses pendidikan itu sendiri.
Sekolah, sadar atau tidak, sedang melakukan dosa terhadap membaca. Membaca dipaksa tunduk pada logika hasil. Tidak ada waktu untuk berhenti, merenung, atau meragukan isi teks. Yang penting adalah apa yang mungkin keluar di soal.
Akibatnya, siswa terbiasa membaca tanpa berpikir. Mereka mencari kata kunci, bukan makna. Mereka menghafal definisi tanpa memahami konteks. Membaca menjadi aktivitas mekanis yang hampa.
Kondisi ini juga memengaruhi cara guru mengajar. Banyak guru terjebak dalam tekanan sistemik. Mereka dituntut mencapai target nilai, bukan target pemahaman. Waktu kelas habis untuk latihan soal, bukan diskusi.
Dalam situasi seperti itu, pertanyaan kritis sering dianggap gangguan. Diskusi dianggap pemborosan waktu. Membaca mendalam dianggap tidak efisien. Yang diutamakan adalah strategi lulus.
Roy Martin Simamora dalam “Pendidikan dan Pentingnya Berpikir Kritis” (Kompas, 24 Mei 2023) menekankan bahwa pendidikan yang gagal menumbuhkan berpikir kritis akan melahirkan generasi yang rapuh menghadapi kompleksitas dunia. Mereka mungkin unggul di ruang ujian, tetapi gagap di ruang kehidupan.
Berpikir kritis tidak lahir dari hafalan. Ia tumbuh dari proses membaca yang perlahan, reflektif, dan dialogis. Ia membutuhkan ruang untuk salah, untuk ragu, dan untuk bertanya.
Namun sekolah modern justru memusuhi keraguan. Keraguan dianggap kelemahan. Padahal dari keraguan itulah pemahaman sejati bermula.
Dalam banyak kasus, siswa yang gemar membaca dan berpikir mendalam justru tersingkir. Mereka dianggap lambat. Mereka kalah dari siswa yang cepat menghafal. Sistem memberi sinyal jelas: kecepatan lebih penting daripada kedalaman.
Motivasi belajar pun berubah. Dari rasa ingin tahu menjadi rasa takut. Dari keinginan memahami menjadi keinginan lulus. Belajar kehilangan kegembiraannya.
Riset Edward L. Deci dan Richard M. Ryan tentang Self-Determination Theory menunjukkan bahwa dominasi motivasi ekstrinsik seperti nilai, peringkat, dan imbalan eksternal dapat melemahkan motivasi intrinsik. Siswa belajar bukan karena dorongan ingin tahu, tetapi karena mengejar angka dan pengakuan formal. Ketika penghargaan eksternal menjadi pusat, minat alami terhadap pengetahuan perlahan terkikis.
Ketika angka menjadi tujuan, membaca pun berubah menjadi beban. Buku tidak lagi hadir sebagai sahabat, melainkan sebagai ancaman evaluasi. Membaca tidak lagi membuka dunia, tetapi membuka kecemasan.
Kritik terhadap sistem semacam ini juga muncul dalam kajian akademik yang lebih luas. Alfie Kohn, dalam berbagai telaah kritisnya tentang pendidikan berbasis standar dan tes, serta sejumlah artikel dalam jurnal seperti Educational Researcher dan Journal of Educational Psychology, mencatat bahwa orientasi pendidikan yang terlalu kuantitatif telah mengerdilkan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan direduksi menjadi proses administratif dan pengukuran, alih-alih proses humanistik yang menumbuhkan pemahaman, refleksi, dan makna.Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi pikiran. Tempat di mana membaca berarti berdialog dengan gagasan. Tempat di mana berpikir berarti menjelajah, bukan sekadar mengulang.
Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi pikiran. Tempat di mana membaca berarti berdialog dengan gagasan. Tempat di mana berpikir berarti menjelajah, bukan sekadar mengulang.
Namun realitasnya, banyak sekolah justru menjadi ruang kompetisi yang sunyi. Setiap siswa sibuk mengejar angka masing masing. Tidak ada percakapan intelektual. Tidak ada kegembiraan intelektual.
Ironisnya, dunia di luar sekolah tidak bekerja seperti soal pilihan ganda. Masalah kehidupan jarang memiliki satu jawaban benar. Dunia membutuhkan kemampuan membaca situasi, menafsirkan informasi, dan mengambil keputusan reflektif.
Siswa yang dibesarkan dalam budaya ujian sering kali kesulitan menghadapi ambiguitas. Mereka mencari jawaban pasti di dunia yang tidak pasti. Mereka menunggu instruksi di dunia yang menuntut inisiatif.
Tekanan global seperti peringkat internasional dan tes komparatif turut memperparah keadaan. Sekolah berlomba mengejar skor, bukan kualitas berpikir. Pendidikan menjadi ajang lomba, bukan proses pemanusiaan.
Padahal membaca yang sejati adalah kegiatan yang melatih kesabaran, empati, dan daya analisis. Membaca mengajarkan bahwa dunia tidak hitam putih. Bahwa kebenaran sering kali berlapis.
Ketika sekolah mengabaikan hal ini, ia bukan hanya gagal mendidik. Ia mencederai masa depan. Ia melahirkan generasi yang cerdas secara teknis tetapi miskin kebijaksanaan.
Dosa sekolah kepada membaca bukan dosa kecil. Ia adalah pengkhianatan terhadap inti pendidikan. Ketika membaca direduksi menjadi alat ujian, pendidikan kehilangan jiwanya.
Sudah waktunya sekolah berhenti menuhankan hasil. Angka boleh ada, tetapi bukan segalanya. Ujian boleh digunakan, tetapi bukan tujuan akhir.
Yang perlu dipulihkan adalah penghargaan terhadap proses berpikir. Terhadap membaca yang perlahan. Terhadap pertanyaan yang belum punya jawaban.
Pendidikan yang sehat tidak takut pada jeda. Tidak alergi pada keraguan. Tidak tergesa mengejar hasil.
Jika sekolah kembali menghormati membaca sebagai proses berpikir, bukan sekadar strategi lulus, maka pendidikan akan kembali menemukan martabatnya. Dan siswa tidak lagi gemetar di hadapan kertas ujian, karena mereka telah belajar memahami, bukan sekadar mengingat.(*)
Lubuklinggau, 9–10 Januari 2026
____
Daftar Pustaka
Biesta, G. (2010) Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
Brookhart, S.M. (2010) How to assess higher-order thinking skills in your classroom. Alexandria, VA: ASCD.
Campbell, D.T. (1976) Assessing the impact of planned social change. Hanover, NH: Dartmouth College.
Deci, E.L. and Ryan, R.M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
Deci, E.L., Koestner, R. and Ryan, R.M. (1999) ‘A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation’, Psychological Bulletin, 125(6), pp. 627–668.
Gehl, J. (2011) Life between buildings: Using public space. Washington, DC: Island Press.
Kohn, A. (1999) Punished by rewards: The trouble with gold stars, incentive plans, A’s, praise, and other bribes. Boston: Houghton Mifflin.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019) PISA 2018 results: What students know and can do. Paris: OECD Publishing.
Ryan, R.M. and Deci, E.L. (2000) ‘Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions’, Contemporary Educational Psychology, 25(1), pp. 54–67.
Shafa, A. (2023) ‘Pendidikan yang membodohi: Mengapa sistem kita gagal mencerdaskan’, Kumparan, [online]. Available at: https://kumparan.com
Simamora, R.M. (2023) ‘Pendidikan dan pentingnya berpikir kritis’, Kompas, 24 May.
TeachHub. (2024) ‘A critical look at standardized testing’, TeachHub, [online]. Available at: https://www.teachhub.com
Zubaidah, S. (2016) ‘Keterampilan abad ke-21: Keterampilan yang diajarkan melalui pembelajaran’, Jurnal Pendidikan, 1(1), pp. 1–10.
4 Comments
efek dari pendidikan yang berpaku kepada angka ini tearsa sekali efeknya pada hidup saya sekarang
ada saran bacaan untuk orang yang pikirannya hanya berkutat pada angka dan ranking kak ben?
Cobalah baca karya naratif. Tidak harus karya sastra. Mungkin bisa mulai dengan serial Chicken Soup.
Tulisannya kena banget bang Ben 🥹 Sekolah sering bikin membaca cuma jadi alat buat cari jawaban, bukan buat mikir dan menikmati prosesnya
makasih banyak, Dias