Sebab Diam Terlalu Lama Menciptakan Jarak
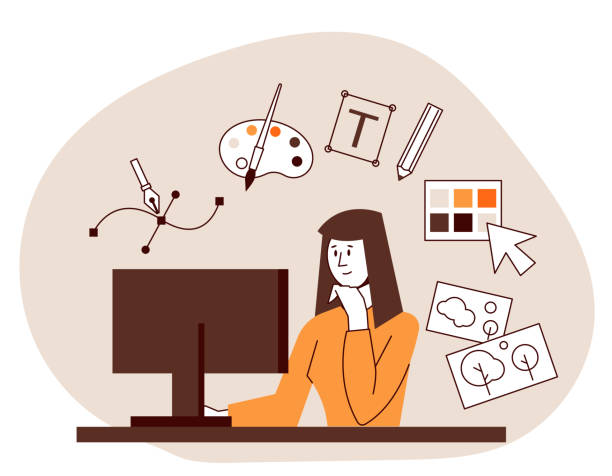
Sumber:https://www.istockphoto.com/id/ilustrasi/kartunis-seniman
Menulis adalah upaya menyelematkan diri dari kebisuan sendiri.
oleh Benny Arnas
Pada sebuah sore yang tampak biasa, seorang perempuan duduk di ruang tamu sambil menggenggam cangkir teh. Ia menatap suaminya yang sibuk menatap layar ponsel. Tak ada pertengkaran, tak ada suara tinggi—hanya diam panjang yang menggantung di antara mereka. Perempuan itu sudah lama menahan kecewa atas perhatian yang berkurang, tapi memilih bungkam demi menjaga suasana rumah tetap “baik-baik saja.” Hingga suatu hari, ketika ia menemukan piring kotor dibiarkan di meja makan, kemarahannya meledak. Suaminya tertegun, tak mengerti kenapa hal kecil bisa menjadi badai. Padahal yang meledak bukan piring kotor, melainkan luka yang terlalu lama disimpan.
Kita mengenal banyak kisah seperti itu, bahkan mungkin mengalaminya. Dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan, diam sering dipilih sebagai jalan aman. Ia memberi ilusi damai, padahal diam yang menekan justru memupuk bara. Ada keyakinan lama yang sulit dipatahkan: bahwa menahan diri selalu lebih baik daripada mengungkapkan perasaan. Tetapi waktu membuktikan, tidak semua diam membawa tenang. Sebagian justru membuat luka berurat, menjadi semacam racun halus yang perlahan merusak dalam sunyi.
Al-Ghazali pernah menulis dalam Ihya’ Ulumuddin, bahwa diam bisa menjadi cahaya bila ia menjaga keburukan, namun bisa pula menjadi kegelapan bila ia menunda kebenaran. Artinya, tidak setiap keheningan adalah kebijaksanaan. Ada diam yang menenteramkan, ada diam yang menunda penyembuhan.
Penelitian psikologi komunikasi modern mengonfirmasi intuisi para pemikir lama itu. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh James J. Gross dan Oliver P. John dari Stanford University (2003), berjudul “Individual Differences in Two Emotion Regulation Processes: Implications for Affect, Relationships, and Well-being”, menunjukkan bahwa menekan emosi (emotional suppression) berkorelasi dengan tingkat stres yang lebih tinggi, hubungan sosial yang lebih buruk, dan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Dengan kata lain, bukan konflik yang berbahaya, tetapi konflik yang tak pernah diucapkan.
Menulis: Cara Halus Mengurai Kepala
Bagi banyak orang, bicara terasa menakutkan. Bukan karena tak punya kata, tapi karena takut salah menempatkannya. Takut disalahpahami, takut melukai, atau sekadar tak tahu harus mulai dari mana. Di situlah menulis menemukan ruangnya: sebagai cara halus untuk berbicara tanpa harus ditatap.
Menulis memungkinkan seseorang menumpahkan isi kepala tanpa interupsi. Di sana, kekacauan bisa diatur ulang; kesedihan bisa dilihat dari jarak aman. Naguib Mahfouz, novelis Mesir peraih Nobel Sastra, pernah menulis bahwa menulis adalah cara manusia “menyusun kembali dunia yang kacau di dalam dirinya.” Dan memang demikian: di tengah dunia yang terus menuntut kecepatan dan kepura-puraan, menulis memberi ruang untuk lambat, untuk jujur.
Psikolog James W. Pennebaker dari University of Texas menghabiskan lebih dari dua dekade meneliti dampak menulis terhadap kesehatan mental. Dalam riset klasiknya pada tahun 1986, ia menemukan bahwa peserta yang menulis tentang pengalaman emosional mereka selama 15–20 menit per hari menunjukkan peningkatan fungsi imun dan penurunan kunjungan medis. Penelitian lanjutan (1997, Journal of Consulting and Clinical Psychology) memperkuat temuan ini: menulis membantu seseorang memahami, bukan sekadar mengulang, peristiwa emosional yang dialami. Melalui tulisan, seseorang belajar menafsir ulang pengalamannya: mengubah luka menjadi makna.
Menulis, dengan demikian, bukan sekadar kegiatan intelektual, melainkan juga bentuk perawatan diri. Ia adalah proses berpikir yang disertai kejujuran. Saat seseorang menuliskan perasaannya, ia bukan hanya sedang menyalurkan emosi, tapi sedang memetakan pikirannya yang berantakan. Dengan menulis, kita memaksa diri untuk memilih kata. Dan dalam memilih kata, kita sekaligus memilih cara berpikir.
Rumi, penyair Persia yang sering disebut sebagai “tukang tenun hati,” menulis: “Kata-kata adalah jembatan bagi hati-hati yang terpisah.” Kadang, hati yang terpisah itu bukan hati dua manusia, melainkan hati dan pikiran di dalam diri yang sudah lama tak saling bicara. Menulis menjadi jembatan untuk mempertemukan keduanya—tanpa pertengkaran, tanpa perlu keberanian publik, cukup keberanian sunyi di depan selembar kertas.
Keberanian untuk Mengucapkan Luka
Menulis membantu seseorang menyiapkan keberanian berbicara, tapi lebih dari itu: menulis adalah bentuk berbicara yang sudah cukup pada dirinya sendiri. Ia tidak selalu bertujuan menyampaikan pesan kepada orang lain; sering kali, ia justru cara berdialog dengan diri sendiri. Dalam setiap kalimat yang ditulis dengan jujur, seseorang belajar menghadapi bagian dirinya yang selama ini dihindari.
Luka yang ditulis tidak selalu sembuh, tapi setidaknya berhenti berputar di kepala. Ketika seseorang memberi nama pada rasa sakitnya, ia sudah mengambil langkah pertama untuk memahaminya. Al-Ghazali pernah menulis bahwa manusia yang tidak mengenali isi pikirannya akan menjadi tawanan dari pikirannya sendiri. Dengan menulis, kita berhenti menjadi tawanan. Kita menjadi saksi bagi diri sendiri.
Hafez, penyair Persia abad ke-14, menulis dengan lembut: “Ketika kau tak berani bicara, pena di tanganmu akan berbicara untukmu. Biarkan ia menulis sampai hatimu selesai berdebat dengan dirinya sendiri.” Mungkin di situlah inti keberanian sejati: bukan dalam berteriak paling lantang, tapi dalam berani menulis paling jujur.
Karena diam terlalu lama hanya menciptakan jarak. Ia menebal seperti kabut, hingga kita lupa wajah orang yang kita cintai, lupa suara hati kita sendiri. Menulis memberi jalan keluar tanpa harus berteriak; memberi arah pada emosi tanpa harus mengurungnya.
Pada akhirnya, setiap manusia butuh ruang untuk mengurai isi kepalanya. Dan tidak semua ruang itu bisa ditemukan dalam percakapan. Ada luka yang baru bisa disembuhkan dalam bentuk tulisan. Sebab menulis, seperti kata Mahfouz, bukan hanya tentang mencatat dunia, melainkan tentang menyelamatkan diri dari kebisuannya sendiri.(*)
Lubuklinggau, 24 Oktober 2025
4 Comments
Betul sekali
Bagus banget kata-kata dari Hafez itu. Dari sekian banyak hobi/kepandaian, aku bersyukur nyangkutnya di nulis. Jelas gak sehabat Bang Benny, tapi setidaknya sejauh ini kemampuan nulis ini udah bermanfaat ke banyak hal. Paling sederhana, kalau dizalimin orang, bisa ungkapkan lewat kata dengan lebih runut dan baik. Jadi, valid kalau luka bisa dikikis sedikit dengan menulis itu.
Menulis menjadi “ruang aman”, tempat hati bisa berdebat dan “selesai” dengan dirinya sendiri, tanpa harus takut pada penilaian atau interupsi, bisa menjadi terapi dan klarifikasi diri.
menyelamatkan diri dari kebisuan