Meminang Fatimah
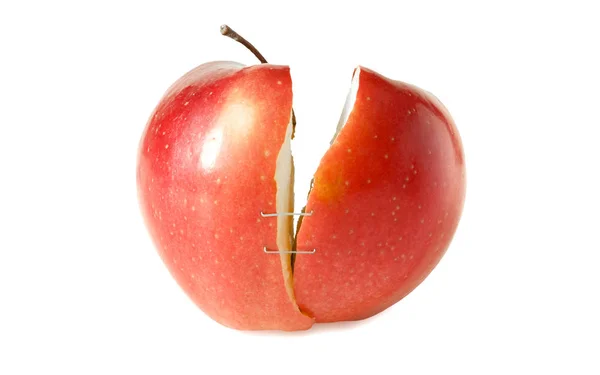
Termaktub dalam kumpulan cerpen Meminang Fatimah (Exotislam, 2009)
Ketika SMA, saya pernah berpacaran lima kali (tiga yang terakhir saya jalani bersamaan ketika duduk di kelas dua). Percaya atau tidak, saya selalu disalip pacar-pacar saya dalam mengungkapkan rasa suka. Walaupun begitu, saya selalu mendahului mereka ketika memutuskan hubungan. Saya tak tahu, harus bangga atau malu dengan kenyataan ini. Tapi bagaimanapun, saya merasa besar kepala juga akhirnya. Sejak itu, saya selalu gengsi untuk menunjukkan rasa suka kepada gadis yang saya sukai, termasuk sekadar menceritakannya kepada teman dekat sekalipun. Saya pongah dengan ‘prestasi’ itu.
Lima tahun kemudian, setelah masa kuliah saya lalui tanpa pacaran(*), ‘penyakit’ besar kepala itu masih saya idap. Hal itu pula yang menyebabkan saya hakkul yakin kalau Fatimah merasakan apa yang saya rasakan. Bukan, saya bukan sekadar yakin kalau dia juga mengingat saya sebagai teman SMA-nya. Lebih dari itu, pertemuan tak sengaja di pengajian umum beberapa hari yang lalu, telah membuat pandangan kami bertabrakan hingga cairan merah bernama asmara tumpah membasahi dada kiri saya, hingga menerbitkan candu untuk selalu melihat wajahnya, hingga membuat saya percaya bahwa jodoh saya sudah dekat: Seorang gadis yang baru saja meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang!
Dan … Tuhan pun seolah mengabulkan keinginan yang tak pernah berani saya cuatkan dalam doa itu: kami kerap bertemu secara tak sengaja di sejumlah tempat—di pasar, di pusat perbelanjaan, di rumah sakit, di sekretariat sebuah partai Islam, atau di tempat lainnya. Mata kami kerap beradu-pandang dalam waktu yang tidak dapat dikatakan sebentar. Entah, saban melihat matanya, saya berubah menjadi besi yang tersedot oleh pesonanya. Saya yakin sekali, ada magnet yang diam-diam bersembunyi di balik retinanya. Ah, bagaimana bisa saya menjadi semelankolik ini!
O ya, saya tak ingin menjadikan perasaan ini berat sebelah. Maka, dengan semua spekulasi yang menjelma bom atom harapan yang siap meledak itu, saya percaya bahwa dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Mungkin, agak lebih tepat saya nyatakan, bahwa dia juga mengetahui bahwa saya memendam perasaan suka yang tak terjelaskan, atau dia malu karena saya mengetahui dia yang justru memendam perasaan itu, atau yang lainnya adalah; sebagai seorang perawan, dia sedang mengangkasa di antara awan-awan guava sebab mengetahui bahwa kami memiliki perasaan yang sama: saling jatuh cinta! Ou ou ou!
Jadi?
Jadi, apalagi yang dinanti?
Ups!
*
Saya pernah mengatakan pada kedua orangtua yang amah alias awam perihal masalah agama, bahwa mungkin sudah saatnya saya dilepas ke laut kehidupan dengan perahu sendiri. Saat itu, masih saya ingat jelas, bagaimana raut muka mereka: sedikit terkejut, tentu saja. Saya tahu, mereka tentu heran, mengapa saya tiba-tiba mengutarakan hal ini.
Ya, di mata mereka, saya relatif tertutup bila membincangkan perkara asmara sejak menjadi seorang ikhwan—begitu istilah orang-orang dalam liqa, perkumpulan pengajian kecil, untuk menyebut saudara laki-laki. Salah satu sebabnya: sejak kuliah, orangtua saya tak pernah melihat saya berpacaran, apalagi mengajak calon menantu, ke rumah mungil kami di utara Lubuklinggau. Mereka tahu benar, sejak jadi mahasiswa, anak sulungnya jadi sangat alim, jadi ikhwan. Bahkan Ayah, dengan ragu-ragu, sempat bertanya, apakah hal ini saya utarakan lantaran tak ingin dilangkahi Amir, adik saya yang usianya hanya berjarak satu setengah tahun dengan saya, yang sejak tahun lalu sudah berkoar-koar bahwa setelah diwisuda dari Universitas Sriwijaya tahun ini, hendak meminang Sisca, gadis yang sudah dua tahun dipacarinya. Ibu juga sempat mengingatkan agar saya tidak gegabah dengan keinginan itu.
“Nikah itu gak main-main,” ujarnya serius. Ah, Ibu bahkan terkesan ‘menduga’, niat saya itu terprovokasi oleh teman-teman liqa yang sebagian besar sudah menikah.
Saya heran, Ayah-Ibu justru tidak bertanya perihal, yang menurut saya, lebih penting, seperti: “Siapa wanita itu?; Sudah berapa lama kau mengenalnya?; Kapan kau akan mengenalkannya pada kami?; Dan masih banyak lagi rupa-rupa pertanyaan yang menurut saya lebih pantas.
*
Jauh sebelum mawar merah itu menguncup di lubuk hati, saya juga pernah meminta pendapat Mufti, satu-satunya teman pengajian yang memiliki nasib sama dengan saya: belum menikah. Sudah saya duga, ia akan mendukung niat saya untuk naik pelaminan. Maklum, dia sudah menganggap saya seperti kakaknya sendiri.
“Menikahlah, Kak, biar saya tak melangkahimu,” katanya dengan senyum dikulum.
Dan sore ini, dipayungi langit berwarna oranye, dia kembali membuka materi itu.
“Apalagi yang ditunggu, Kak?”
Saya terdiam.
“Umur sudah dua lima. Finansial? Jangan bercanda deh!”
Saya menghela napas.
“Kakak baru buka cabang toko komputer yang baru di Tabapingin, kan?”
Saya tahu, ujung-ujungnya Mufti akan menyarankan saya untuk secepatnya mengajukan proposal pada murabbi, guru pengajian kami. Wuiihh! Mufti, Mufti. Andai kamu tahu, bahwa saya sudah sangat alergi dengan yang namanya proposal-proposalan, yang akhirnya akan mengerucut pada satu kata pra-lamaran: ta’aruf.
Ta’aruf, ta’aruf. Pengajian telah mengakrabkan saya dengan istilah Arab yang berarti ‘perkenalan’ untuk mengetahui masing-masing pribadi dengan adab-adab islami tersebut. Namanya juga ‘perkenalan’, jadi kedua belah pihak belum (sepenuhnya) mengenal satu sama lain. Dengan ditemani masing-masing muhrim dan mahrom, murabbi atau murabbiyah (untuk guru pengajian perempuan), dan orang yang dapat dipercaya lainnya, dari balik pembatas—biasanya kain tidak tembus pandang, masing-masing akan menjelaskan profilnya (biasanya pihak wanita telah mengetahui profil si laki-laki karena telah membaca proposal sebelumnya). Setelah itu, memakan waktu beberapa hari sampai satu-dua minggu, akan didapat jawaban dari pihak wanita. O ya, ada juga pihak wanita yang mengajukan proposal kepada pihak laki-laki. Walaupun saya melihatnya sebagai ketaklaziman, namun cukup dimaklumi pula, bahwa ‘emansipasi’ pun telah menyerang gadis-gadis berjilbab itu.
Pembicaraan itu tak selesai. Mengambang saja. Mufti bahkan tidak bertanya tentang kriteria calon istri yang saya inginkan, atau bahkan meminta saya menyebutkan siapa kira-kira akhwat, gadis yang ingin saya pinang itu. Dalam hal ini, tak lebih-tak kurang, setali tiga uang saja dia dengan Ayah dan Ibu.
*
Sungguh, bukan karena teknis ta’aruf yang rada ribet itu yang membuat saya tak ingin menjalaninya. Bukan pula kesan ketidakadilan bahwa biasanya pihak wanita telah membaca proposal itu sebelumnya, sehingga pihak laki-laki terkesan terlalu meminta-minta—atau ada alasan-alasan lainnya, namun lebih pada kelelahan psikologis yang mendera saya.
Dulu, waktu masih kuliah, ditemani murabbi, tiga kali saya menjalani ta’aruf. Semuanya, ya semua, ditolak. Saya ulangi: di-to-lak! Dan saat itu, semua-mua alasan yang saya dapatkan dari murabbi tidak mampu memuaskan saya.
“Akh, cobalah berpikir realistis. Vani itu …”
“Dia lebih tua dua tahun dari saya!” potongku sengit. Entah saya tak tahu bagaimana bisa selancang itu berbicara pada Ustaz Alim, murrabi saya kala itu.
“Bukan, Akh,” jawabnya tenang.
“Ooo … karena dia baru saja menyelesaikan ko-ass-nya di Medan dan sekarang sudah bergelar dokter?”
Ustaz Alim terdiam.
“Jadi?” desak saya dengan bahu bergetar.
“Ya.”
“Oohh …”
“Sabar, Akh. La tahzan.”
“Mungkin seharusnya dulu saya tidak memilih kuliah di Fakultas Pertanian ya, Taz?”
Ustaz Alim tersenyum getir dan memeluk saya dengan lembut. Saya menangis.
Itu adalah ta’aruf ketiga saya. Lebih tepatnya lagi, yang terakhir bagi saya. Dulu, Rina, adik tingkat di Fakultas MIPA, pernah meminta saya menunggu sampai ia menyelesaikan Magister-nya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat itu saya tak memiliki stok sabar yang cukup untuk menunggunya empat tahun—itu pun kalau ia dapat menyelesaikan S2-nya tepat waktu, lha kalau malah molor? Ya, kala ta’aruf dia duduk di semester lima program S1-nya. Ketika saya menyampaikan keberatan saya dan mengajak menikah lebih dulu, Rina menggelengkan kepala.
Anna adalah memori kelam ta’aruf saya selanjutnya. Saat itu, saya baru saja meraih gelar sarjana. Dan, mendung itu kembali singgah. Proposal saya ditolak. Anna sudah dipinang Ali, karib saya yang baru saja diterima bekerja di PT. Semen Padang. Saat itu, Ustaz Alim berkali-kali mentausiyahi saya agar mengambil hikmah dari semua ketetapan langit yang ‘sepertinya’ tak memihak saya.
Alhamdulillah, saat itu saya masih bisa menyemringahkan air muka dan menguatkan hati untuk mengikhlaskan semuanya. Sampai Vani–Gate itu datang dan robohlah semua bangunan ketsiqahan saya terhadap ta’aruf. Bahkan dua bulan sebelum memutuskan meninggalkan Padang untuk kembali ke Lubuklinggau, liqa tak pernah saya hadiri lagi.
*
“Kak, ada berita gembira!”
“Apa itu, Muft?” sahut saya antusias.
“Ada proposal untuk Kakak.”
“Kegiatan apa?”
“Allah mendengar doamu, Kak.”
“Maksudmu?” Saya mengernyitkan dahi.
“Sudahlah jangan berlagak pilon. Kakak ditunggu ustaz sekarang di rumahnya.”
Klek.
“Halo, halo?!”
Sambungan terputus.
Saya bergegas meluncur ke kediaman Ustaz Ardi, murabbi saya saat ini. Benak saya masih bertanya-tanya tentang maksud kata-kata Mufti tadi. Apa hubungan proposal itu dengan Ustaz Ardi?
Di kediamannya, Ustaz Ardi menyambut saya dengan wajah penuh seri. Dan … betapa fobianyakah saya pada kata itu, sampai pikiran saya tiada berdaya lagi menghubungkan kata-kata Mufti di telepon tadi? Ya Rabbi, ta’aruf lagi, ta’aruf lagi. Sebelum Ustaz Ardi menyelesaikan kalimatnya, saya menyampaikan keberatan.
“Ada apa, Akh?” tanyanya penasaran. “Tidakkah Anta sudah mumpuni untuk menunaikannya?”
Saya masih memikirkan formasi kata-kata yang sebaiknya.
“Tidakkah Anta ingin menggenapkan separuh agama?”
“Iya, Taz.”
“Lalu?”
“Tidak dengan ta’aruf, Taz.” Tak berani saya tatap wajah Ustaz Ardi ketika menyampaikan kata-kata itu. Sungguh, saya tak ingin murabbi saya salah paham. Maka, mengalirlah cerita lama itu.
“Perbanyaklah zikir, wahai Akhifillah.”
Saya mengangguk pelan. Sungguh, rasanya saya ingin menangis.
“Jangan tinggalkan yang wajib. Perbanyak yang sunnah. Istikharahlah. Dia tidak pernah pilih kasih. Dia tak pernah menzalimi hamba-Nya. Banyak-banyaklah bermuhasabah.”
Saya amini semua nasihatnya. Alhamdulillah, Ustaz Ardi dapat memahami keadaan saya.
*
Tentu saja saya ingin menggenapkan dien. Siapa yang tak ingin menikah ketika usia telah mumpuni dan pekerjaan yang baik seperti ini. Tapi demi Allah, bukan menafikan ta’aruf, saya hanya tak ingin masuk lubang untuk yang keempat kalinya. Sakit, sakiit, sakiiit sekali rasanya.
“Mengapa Kakak menolaknya?”
“Lebih baik kau tanya murabbi kita, Muft?”
“Atau Kakak tidak sreg dengan akhwat itu?”
Saya diam. Bahkan saya belum tahu siapa dia.
“Atau Kakak, maaf, sudah punya akhwat incaran yang lain?” wajah Mufti memerah. Tampaknya dia menyesal telah menanyakan hal itu.
Saya tersenyum, masam.
“Maafkan saya, Kak.”
Apa yang kaukatakan benar. Saya memang tengah mengincar akhwat lain. Itulah suara yang bergema dalam lorong batin saya.
“Kak.“
“Ehh … ehh ….”
“Kok diam, Kak?”
“Eh, tidak. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Muft.”
“Tapi …?”
“Sudahlah Mufti, jangan merasa terhalangi oleh saya.”
“ ….”
“Jangan eratnya ukhuwah kita justru membuatmu merasa tak keenakan melangkahi saya. Tafadhal, silakan, jangan mengendurkan niatmu untuk walimahan kalau jodohmu sudah sampai. Kakak pasti ikut gembira kalau itu benar adanya, hehe ….” Saya mencoba mencairkan suasana.
Mufti mengangguk-angguk. Matanya tidak bisa berbohong. Dia mengasihani saya. Dan saya benci itu. Dia pamit dengan ketakmengertian yang masih menggelayutinya. Maafkan saya, Saudaraku. Banyak hal tentang saudaramu ini yang tak harus kaupahami sepenuhnya.
*
Akhirnya berhasil juga saya meyakinkan orangtua. Sebenarnya mereka tak punya alasan yang cukup kuat untuk tidak merestui niat baik saya, apalagi bila mau dibandingkan dengan Amir yang belum jelas juntrungannya setelah tamat kuliah, sungguh saya jauh lebih layak menikah lebih dulu. Apalagi Amir juga mendukung saya itu, walaupun diselipi catatan:
“Satu-dua bulan setelah itu, Amir juga minta ditunangin dengan Sisca ya, Yah. Pengennya sih langsung kawin, tapi katanya pamali kalau ngawinin dua anak dalam setahun,” katanya dengan nada mengultimatum.
Satu tugas telah selesai. Tapi saya mendadak galau. Keraguan menyerang. Benarkah Fatimah ingin menerima pinangan saya? Oh tidak, lebih tepatnya, telahkah Fatimah ingin saya pinang tanpa ta’aruf?
Ah, walaupun proses pra-pinangan itu telah mentradisi dalam kultur liqa, tapi bukankah hal yang paling penting adalah kedua belah pihak mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut saya, tiga tahun kami di SMA dulu telah cukup mewakili proses ta’aruf itu. Saat itu, ketika belum berjilbab seperti saat ini, Fatimah telah tampak sebagai wanita yang anggun dan bertabiat baik. Ah sayang, saya yang menantikannya mengungkapkan perasaan lebih dulu, justru tak mau mengalah. Hingga usai SMA pun, saya tak sempat mengutarakan perasaan itu, padahal saya sangat yakin, dia juga menyukai siswa tampan dan cerdas seperti saya. Ah, mengingat itu, saya makin kagum padanya. Fatimah telah memilih cara yang benar. Ya, bila saat itu dia ‘menembak’ saya seperti pacar-pacar terdahulu, hari ini saya tidak akan kesetrum seperti ini.
Saya pikir Fatimah pun cukup mengenal siapa saya. Bukankah kami satu kelas ketika saya terpilih sebagai Siswa Teladan Kabupaten saat itu?; bukankah dia juga tahu bahwa saya satu-satunya siswa dari SMA kami yang dikirim ke Malaysia untuk mengikuti program pertukaran pelajar selama dua bulan?; dan saya pikir, dia juga sudah mengetahui reputasi saya saat ini: seorang wiraswastawan jual-beli komputer yang sedang menanjak, plus mengepalai beberapa LSM yang concern terhadap masalah sosial dan pendidikan. Ah, dia tidak terlalu buta akan hal itu!
Satu bulan berlalu sudah. Sudah cukup rasanya saya memantapkan niat. Apalagi dari teman liqa-nya, saya sudah mendapat nomor ponsel Fatimah. O ya, saya sengaja meliburkan diri dari liqa dan mengganti kartu GSM di ponsel. Bahkan, saya sangat bersyukur, ketika Ibu menyampaikan bahwa beberapa kali Ustaz Ardi, Mufti, atau teman-teman liqa datang ke rumah ketika saya sedang keluar.
“Kata mereka HP-mu gak bisa dihubungi. Kamu ganti nomer?” tanya Ibu ingin tahu.
Saya berbohong pada Ibu. Ya, saya tak ingin Ibu memberikan nomor GSM baru saya pada mereka. Oh Ibu, sungguh, anakmu ingin mempersiapkan semuanya dengan tenang dan matang. Saya pikir, lebih baik liqa saya ikuti setelah urusan lamaran ini selesai. Astaghfirullah, semoga hamba tidak termasuk orang-orang yang takabur….
Hari ini telah saya pilih untuk meneleponnya, mengutarakan maksud ini dengan hati-hati. Malam tadi telah saya karang kata-katanya sebaik mungkin. Ya Tuhan …, mengapa tiba-tiba saya merasa sangat cemas. Optimisme itu seakan-akan mengendur. Ya Allah, sejujurnya, saya takut ditolak. Tapi lekas saya kibaskan kekhawatiran itu. Ya, saya harus memulai semua ini. Sekarang juga. Bismillah.
Ups! Saya embuskan napas dalam-dalam. Hampir saya tekan nama “Fatimah” di daftar kontak ponsel, kalau saja gendang telinga saya tidak menangkap suara Mufti yang tengah bercengkerama dengan Ibu di beranda depan. Ah, dia pasti menanyakan ketidakhadiran saya di beberapa pertemuan liqa
Saya menahan langkah di balik daun pintu.
“Wah, insya Allah, kakakmu juga mau lamaran dalam waktu dekat, Muft.”
Duuuh Ibu, kok dibocorin. Ini kan masih rahasia.
“Kapan, Bu?” tanya Mufti sambil menyerahkan selembar kertas gloosy.
“Lebih baik langsung saja ngomong dengan kakakmu, ya,” kata Ibu sumringah.
Saya langsung melangkah ke beranda. Seperti biasa, Mufti memeluk saya hangat.
“Ke mana saja, Kak? Ponselnya gak bisa kita hubungi juga. Kok gak pernah nongol di liqa, Kak?”
Hmm, betul kan dugaan saya!
“Nggak, lagi cuti aja, Muft,” jawab saya diikuti tawa kecil. Saya mempersilakannya duduk di bangku panjang beranda.
“Ngaji kok pakai cuti segala,” ujarnya setelah duduk. “Memangnya sibuk apa sih, Kak?” Ia meninju pelan bahu kanan saya yang duduk di sebelahnya.
“Sibuk nyari istri!” jawab saya lalu tertawa.
“O ya? Wah pantas mengalihkan proposal itu ke saya.”
Daging kening saya mengernyit.
“Bener kan ternyata Kakak sudah punya akhwat incaran lain?”
Saya masih nyengir. “Doakan saja, Muft. Tidak lama lagi Kakak bakal lamaran,” ujar saya bangga.
“Kamu keduluan, Nak!” Tiba-tiba Ibu menghampiri saya seraya menyerahkan kertas mengilap yang tadi diberikan Mufti. “Ini undangannya Mufti. Jumat nanti ijab-kabulnya.”
Oh, saya sedikit terkejut. Ah, tak apa. Tah sebentar lagi saya akan menyusul.
“Kakak sih, ditelepon gak aktif, di-SMS gak dibalas, didatangi malah gak ada di rumah. Jadinya Mufti gak bisa ngabarin prosesnya yang secepat kilat ini. Padahal banyak yang mau di-sharing ….”
Saya buka kertas berwarna marun itu seraya melirik Mufti yang wajahnya sudah merah buah naga. Pasti perasaan bahagia, bangga, dan sedikit malu sedang melumurinya. Oh, tiba-tiba ada dua jarum yang melesat masuk ke mulut saya. Yang satu menusuk lidah, satunya lagi melintang di tenggorokan saya. Memang tidak mengeluarkan darah, tapi sukses membuat saya kesulitan memproduksi kata-kata. Tak sanggup rasanya saya eja nama mempelai wanita di undangan itu.
“Mmm … pasti Kakak gak nyangka, kan?” Mufti terkekeh kecil. “Kakak sih standarnya tinggi banget. Akhirnya Ustaz Ardi mengarahkan proposal itu pada Mufti. Mmm … atau mentang-mentang akhwat yang ngajuin proposalnya, Kakak jadi nolak …?
Saya tahu, raut muka saya mendadak menjadi putih daging bengkuang.
“Ada apa?” tanya Ibu. Tampaknya ia menangkap keterkejutan di wajah saya.
Mufti pun memandang saya dengan sorot mata tak mengerti.
“Ada apa, Nak? Kok tiba-tiba kamu seperti orang linglung gitu?” desak Ibu.
Saya menggeleng pelan.
“Sudah, Ibu mau ke pasar dulu, beli sayur sekalian beli bahan buat kebaya baru. Kalau nanti kamu mau ngelamar, gak mungkin Ibu masih pakai kebaya yang lama.”
“Gak usah, Bu,” balas saya cepat.
“Lho?”
“Mungkin lebih baik Amir yang duluan, Bu …,” ujar saya seperti bergumam.
“Maksudmu? Lamarannya gak jadi? Kamu sudah menelponnya? Dia menolakmu? Bukannya katamu, kalian sama-sama suka? Siapa sih gadis itu? Ah, tapi memang dasarnya kamu yang gak tegas!” Saya tahu, Ibu sangat bingung dengan sikap saya. Dia sangat kecewa.
Sungguh, saya sangat malu. Bukan saja pada Ibu, tapi juga pada Mufti yang makin bingung dengan cerocosan Ibu.
Mufti bangkit dari duduknya dan buru-buru pamit dengan mengucap salam sekenanya. Sepertinya ia tak ingin menyaksikan kekalahan telak saya. Ah dia tak pantas disalahkan.
Tak berselang lama, Ibu membanting keranjang belanjaannya yang masih kosong di hadapan saya. Tak ketinggalan ia menyumpah serampah sebelum membanting pintu dan melemparkan kertas harum itu pada saya.(*)
Lubuklinggau, September 2008
(*): Kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas telah mempertemukan saya dengan Forum Studi Islam (Forstudi). Pergaulan para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi intrakurikuler kampus itu sedikit banyak memengaruhi saya untuk bertindak lebih positif dan tentu saja lebih islami. Walhasil, saya tak pernah pacaran, punya kelompok pengajian rutin alias liqa atau halaqah, hampir tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid, bisa khatam Quran dua kali setahun, tidak bersalaman dengan nonmuhrim, bahkan tidak menatap mata lawan jenis ketika berbicara. Hingga tahun ketiga kuliah, saya menerapkan semuanya tanpa tedeng aling-aling. Namun di dua semester terakhir, saya merasa ada yang salah dengan prinsip keimanan yang saya jalani. Ya, yang salah adalah perkara “menjalani”-nya, bukan “prinsip”-nya. Saya seolah baru sadar, selama kuliah, saya memiliki sedikit teman. Sebagian besar mereka adalah teman-teman Forstudi. Saya yang awalnya menjaga jarak dengan teman-teman non-Forstudi, akhirnya justru dijauhi. Saya merasa telah angkuh dengan ‘kesucian” yang tiba-tiba menghinggapi saya selama tiga tahun kuliah. Saya merasa belum telat untuk berubah. Saya pun menjalankan prinsip yang saya imani dengan lebih lentur, moderat, dan kompromis. Saya tahu, ada satu-dua kesalahan yang akhirnya tanpa sadar saya lakukan. Namun, saya juga merasa, tidak sedikit manfaat yang saya petik di semester-semester akhir kuliah saya. Paling tidak, hubungan saya dengan teman-teman, dosen, tetangga kos, dan mahasiswa non-Forstudi lebih cair, bersahabat, dan penuh pengertian.