Bagaimana Tetap Membaca dan Menulis meski Sedang Tak Ingin
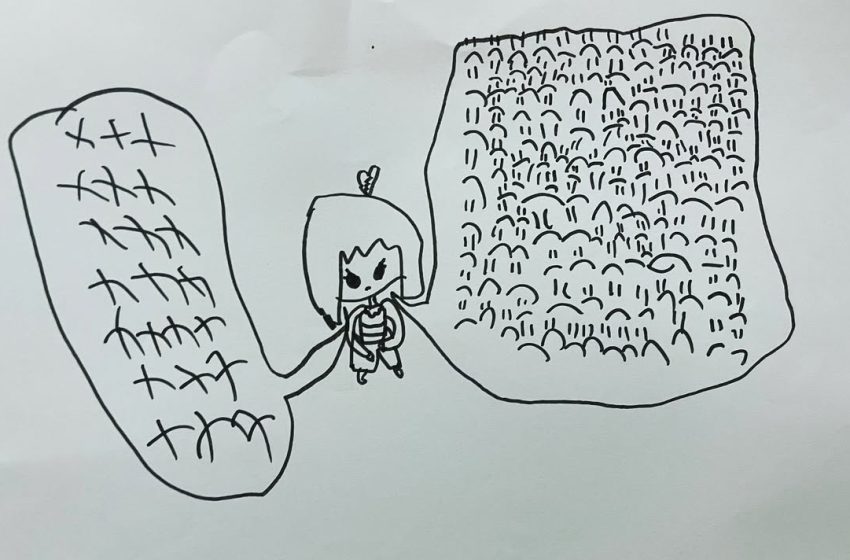
Ilustrasi ole @demauraisyah_arnas
Jam tangan di atas meja kerja mengingatkan saya bahwa waktu tidak bisa dikendalikan, ia hanya bisa dijaga.
OLEH BENNY ARNAS
Suatu pagi di akhir pekan, seorang kawan menulis keluhan di media sosial:
“Tiga minggu tak menulis. Rasanya kosong. Mau mulai, tapi tak ada semangat.”
Banyak yang menimpali dengan saran lembut: “Nikmati saja dulu,” atau “Tunggu mood datang.” Kalimat-kalimat itu terdengar bijak, tapi sering menjadi pembenaran untuk menunda. Padahal, kehilangan kebiasaan menulis biasanya bukan karena kehilangan ide, melainkan kehilangan jadwal.
Setiap orang yang bekerja dengan pikiran—penulis, guru, peneliti, jurnalis—pasti pernah mengalami masa “tak ingin”. Namun, jika kita menunggu suasana hati membaik, kita akan menunggu terlalu lama. Produktivitas, termasuk dalam menulis dan membaca, tidak tumbuh dari mood. Ia tumbuh dari keteraturan.
Setiap pagi pukul sembilan, setelah mengantar anak ke sekolah dan berlari 30 menit, saya menulis. Itu waktu yang saya jaga. Setelah mandi dan membuat kopi, saya duduk di meja kerja, melepas jam tangan, dan meletakkannya di atas meja.
Saya sengaja memakai jam tangan analog, bukan melihat jam di ponsel. Ponsel terlalu mudah mencuri perhatian: satu notifikasi, satu pesan masuk, dan fokus pecah. Jam tangan, sebaliknya, memberi rasa waktu yang tenang. Ia tidak berdering, tidak bergetar, hanya berjalan.
Pukul sembilan hingga zuhur adalah waktu menulis dan membaca. Setelah itu, dunia boleh gaduh. Tapi pagi itu hanya untuk bekerja dengan sunyi. Jadwal itu sederhana, tapi penting: ia mengubah kebiasaan menjadi disiplin.
***
Kita sering menganggap jadwal sebagai batas, padahal jadwal justru menjaga agar kita tidak hanyut dalam kekacauan. Menulis atau membaca hanya saat ingin berarti membiarkan diri ditentukan oleh fluktuasi perasaan—dan perasaan, sebagaimana cuaca, tak bisa diandalkan.
Ungkapan “creative works on mood” sering terdengar manis, tapi sesungguhnya menyesatkan. Tidak ada profesi lain yang bergantung pada mood. Dokter tetap mengoperasi meski lelah, guru tetap mengajar meski pikirannya penuh. Mengapa penulis atau pembaca merasa perlu menunggu suasana hati yang “tepat”?
Kerja kreatif justru menuntut disiplin yang lebih tinggi. Haruki Murakami menulis sejak pukul empat pagi setiap hari selama lima jam, lalu berlari sepuluh kilometer. Ia melakukannya bertahun-tahun tanpa jeda. Tidak ada rahasia, hanya rutinitas. Virginia Woolf menulis dengan kebiasaan yang serupa. Hemingway pun demikian: menulis setiap pagi di meja kecilnya. Mereka tahu, inspirasi datang bukan kepada yang menunggu, tapi kepada yang menyiapkan tempatnya.
Al-Ghazali pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, “Waktu adalah kehidupan; barang siapa menyia-nyiakannya, berarti telah menyia-nyiakan hidupnya sendiri.” Kalimat itu sederhana tapi tajam: disiplin waktu bukan semata urusan produktivitas, melainkan penghormatan pada hidup itu sendiri.
***
Rutinitas juga membantu menekan distraksi. Dalam dunia yang terus memanggil lewat notifikasi, distraksi adalah ancaman paling nyata. Penelitian dari American Psychological Association (2020) menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali fokus setelah terdistraksi oleh ponsel. Satu gangguan kecil bisa memakan waktu setengah jam tanpa terasa.
Dengan jadwal, kita menciptakan batas psikologis yang tegas: otak tahu bahwa ini waktu bekerja, bukan waktu luang. Ketika jam menulis tiba, tubuh pun menyesuaikan diri. Dorongan untuk membuka ponsel atau menonton video singkat berkurang. Kita tahu, ini bukan waktu bermain.
Tanpa struktur waktu, batas antara “kerja” dan “bersantai” kabur. Akibatnya, pekerjaan terasa berat, sedangkan waktu luang justru menjadi ruang kosong yang cepat terisi hal-hal remeh. Dua-duanya tidak menghasilkan apa pun.
***
Bekerja dengan jadwal bukan berarti kehilangan spontanitas. Sebaliknya, jadwal memberi ruang bagi spontanitas yang lebih terkendali. Ketika pikiran sudah terbiasa bekerja pada jam tertentu, ide datang lebih mudah karena otak mengenali pola waktunya.
Riset dari University of Toronto (2019) menunjukkan bahwa rutinitas waktu memperkuat ritme kognitif alias pola internal yang membuat seseorang lebih cepat memasuki kondisi fokus. Keteraturan ini juga menjadi jangkar emosional.
Ketika saya sedang tidak ingin menulis, saya tetap duduk di meja, membuka file terakhir, dan membaca ulang kalimat terakhir yang saya tulis kemarin. Lima belas menit pertama sering terasa sia-sia. Tapi setelah itu, pikiran mulai bergerak. Konsistensi semacam ini membuat saya tetap menulis bahkan di hari-hari berat.
***
Ada masa ketika jadwal saya berantakan karena perjalanan. Dua atau tiga hari tanpa menulis tidak masalah. Tapi ketika jedanya lebih panjang, saya mulai merasa kehilangan arah. Begitu kembali ke meja, saya butuh waktu lebih lama untuk memulihkan ritme. Kalimat terasa kaku, ide macet.
Dari situ saya belajar bahwa jadwal bukan sekadar alat manajemen waktu, melainkan cara menjaga kontinuitas batin. Menulis dan membaca menuntut kedekatan dengan diri sendiri. Jika jeda terlalu lama, jarak itu melebar. Dan jarak itulah yang membuat seseorang merasa “tidak ingin”.
Ali bin Abi Thalib pernah berkata, “Waktu seperti pedang; jika engkau tidak memotongnya, ia akan memotongmu.” Kalimat itu mungkin lahir dari dunia yang jauh dari konsep “deadline”, tapi maknanya tetap relevan: waktu tidak netral. Ia bisa menjadi kawan yang menumbuhkan, atau lawan yang menelan.
***
Kita sering mengira waktu luang memberi kebebasan, padahal ia sering menipu. Waktu luang yang tak diarahkan hanya melahirkan ilusi kesenangan. Kita menonton video “sebentar saja”, lalu setengah jam hilang tanpa hasil. Kita membuka media sosial “sekadar mengecek”, tapi berakhir tersesat di gulungan konten.
Jadwal, sebaliknya, memberi batas dan arah. Dengan batas, kita tahu kapan bekerja dan kapan berhenti. Tanpa batas, kita hanya berpindah dari satu distraksi ke distraksi lain.
Penelitian dalam British Journal of Psychology (2018) menunjukkan bahwa orang dengan rutinitas stabil cenderung lebih fokus dan memiliki kualitas tidur lebih baik. Rutinitas membuat tubuh dan pikiran mengenali ritme harian, sehingga energi tidak terkuras untuk beradaptasi berulang kali.
Jadwal membuat kita tahu kapan harus berhenti dan kapan mulai lagi. Ia menata ritme batin sebagaimana ia menata waktu.
***
Jam tangan di meja kerja saya menjadi simbol kecil dari prinsip itu. Ia mengingatkan bahwa waktu tidak bisa dikendalikan, hanya bisa dijaga. Begitu jam itu saya lepas, artinya saya masuk ke wilayah menulis. Begitu saya memakainya lagi, waktu kerja selesai.
Simbol semacam ini membantu menjaga disiplin. Ia memberi sinyal konsisten bahwa pekerjaan dimulai dan diakhiri dengan sadar. Kebiasaan kecil seperti ini mengubah pola pikir dari “saya harus menulis” menjadi “sekarang waktunya menulis”.
***
Kedisiplinan bukan lawan kreativitas. Justru sebaliknya, disiplin adalah syarat agar kreativitas muncul. Gustave Flaubert pernah menulis: “Be regular and orderly in your life, so that you may be violent and original in your work.”
Keteraturan dalam hidup memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja lebih berani.
Itu pula sebabnya, pekerjaan kreatif seharusnya tidak dianggap istimewa dari pekerjaan lain. Bedanya justru sangat menguntungkan aktivitas membaca dan menulis itu sendiri: kita bisa menentukan jadwalnya sendiri!
***
Menulis dan membaca dengan jadwal bukan perkara mudah. Ada hari-hari ketika tulisan macet atau bacaan terasa berat. Tapi hadir pada jam yang sama, meski tanpa hasil gemilang, jauh lebih berarti ketimbang menunggu mood yang tak pasti.
Yang paling sulit bukan menulis kalimat pertama, melainkan duduk dan membuka halaman kosong. Setelah itu, biasanya pekerjaan berjalan dengan sendirinya.
Pada akhirnya, jadwal adalah cara paling sederhana untuk mengingatkan diri bahwa membaca dan menulis bukan kegiatan ajaib. Ia tidak bergantung pada ilham, melainkan pada kebiasaan yang dijaga.
Setiap kali pukul sembilan datang dan saya duduk di depan meja, jam tangan tergeletak, ponsel terbalik, saya tahu: ini waktu yang saya janjikan pada diri sendiri. Mungkin tulisan hari itu biasa saja, tapi prosesnya menjaga saya tetap utuh di tengah dunia yang mudah tercerai.
Dan mungkin, hanya itu yang dibutuhkan agar seseorang tetap bisa membaca dan menulis—meski sedang tak ingin.(*)
Lubuklinggau, 27 Oktober 2025
6 Comments
Wahhh… Relate bgt sama sy ini bang ben, seniman budak mood 🥲
Telah habis kata membaca ini,
Kok bisa benar ya 🤭
Paket komplit, berkaca pada diri sendiri, “creative works on mood”. Apapun alasannya tidak dibenarkan menulis menunggu mood, ya😁
Duh kayak bisa baca pikiran deh bang, relate.
Terima kasih tulisan pengingatnya Bang untuk saya yang tidak lagi menulis karena sudah jarang membaca.
Ini “cuma” tulisan, tapi “tamparan”nya kerasa bener haha.
Terima kasih, Bang. Sangat inspiratif