Bagaimana Agar Tidak Mudah Bosan Ketika Membaca?
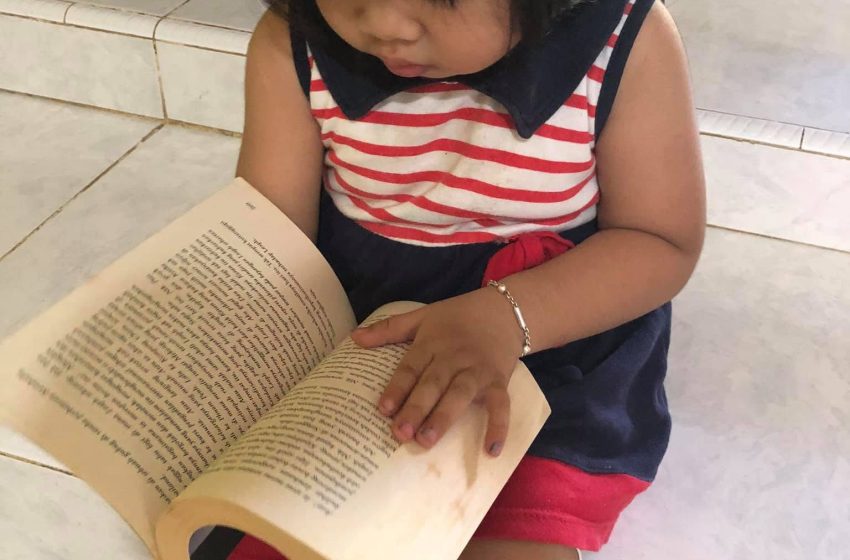
Jangan-jangan bukan salah buku, tapi imajinasimu yang melemah.
Oleh Benny Arnas
Bosan saat membaca sering dianggap tanda bahwa seseorang tidak cukup rajin atau tidak cukup cerdas. Padahal, bisa jadi penyebabnya jauh lebih menarik: bukan pada pembaca atau isi buku, melainkan pada cara teks dan imajinasi saling bertemu. Buku yang bagus pun bisa terasa hambar bila pembaca hanya memosisikan diri sebagai penerima pasif. Sebaliknya, buku yang biasa-biasa saja bisa hidup ketika dibaca dengan cara yang aktif—seolah-olah di dalam setiap kalimat berlangsung percakapan yang hangat antara penulis dan pembacanya.
Dalam dunia literasi, cara membaca seperti itu sebenarnya wajar. Banyak penulis besar yang justru berharap pembacanya “melawan”. Pramoedya Ananta Toer pernah menulis, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat.” Namun yang sering terlupakan adalah bahwa menulis dan membaca pada dasarnya adalah dua sisi dari kegiatan yang sama: dialog batin antara dua pikiran. Ketika membaca Bumi Manusia, misalnya, pengalaman menjadi jauh lebih kuat jika pembaca tidak sekadar mengikuti kisah Minke, melainkan juga mempertanyakan: mengapa ia berpikir seperti itu, mengapa Nyai Ontosoroh bertindak demikian? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadikan membaca sebagai proses berpikir, bukan sekadar kegiatan melahap kata.
Hal serupa berlaku ketika membaca karya pengembangan diri. Buku seperti Atomic Habits karya James Clear atau Man’s Search for Meaning karya Viktor Frankl sering dibaca dengan cara terlalu “sekolahan”—dicatat poin-poinnya, dihafal langkah-langkahnya—tanpa ruang untuk berdialog dengan isi. Padahal pembaca bisa saja tidak sepakat dengan metode yang disarankan, atau ingin menafsirkan ulang berdasarkan pengalaman pribadi. Di sinilah membaca berubah dari rutinitas menjadi proses kreatif: setiap halaman menjadi tempat menguji gagasan.
Bayangkan, misalnya, seseorang membaca The Subtle Art of Not Giving a F*ck karya Mark Manson. Ia bisa saja berhenti di tengah bab dan menulis catatan: “Saya paham maksudnya agar tidak mudah stres, tetapi apakah benar ketenangan batin bisa diperoleh hanya dengan berhenti peduli?” Catatan semacam itu bukan bentuk perlawanan, melainkan tanda bahwa pembaca sedang hidup di dalam teks. Ia sedang menciptakan versi dialogis dari membaca.
Buku pada dasarnya tidak menuntut kepatuhan mutlak. Ia mengundang pembaca untuk berpikir. Karena itu, pembaca perlu menciptakan percakapan imajiner dengan penulisnya. Dalam percakapan itu, pembaca boleh mengkritik, mengajukan pertanyaan, atau menambahkan pandangan pribadi. Ketika membaca Laskar Pelangi, misalnya, mungkin muncul pertanyaan: apakah semangat pendidikan yang digambarkan Andrea Hirata masih relevan di tengah sistem pendidikan hari ini? Atau ketika membaca To Kill a Mockingbird, pembaca bisa bertanya: bagaimana jika kisah tentang keadilan itu terjadi di negeri sendiri? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, membaca menjadi kegiatan yang hidup.
Tapi bagaimana jika semua cara itu tidak berhasil? Apa jadinya jika setiap buku—bahkan yang temanya disukai—tetap terasa membosankan? Mungkin masalahnya bukan pada teks, melainkan pada imajinasi yang melemah.
Sebuah riset dari Emory University berjudul “Short- and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain” yang dilakukan oleh Gregory S. Berns, Kristina Blaine, Michael J. Prietula, dan Brandon E. Pye (2013) menunjukkan bahwa membaca novel mengaktifkan lebih banyak area otak dibanding aktivitas pasif seperti menonton film. Melalui pemindaian fMRI, mereka menemukan peningkatan konektivitas pada area yang berhubungan dengan pemahaman cerita dan pengambilan perspektif—menandakan bahwa otak pembaca bekerja keras membangun gambaran mental dari teks, membentuk warna, suara, dan emosi yang tak ditampilkan secara langsung. Tak heran bila pengalaman membaca terasa lebih “melelahkan”, tetapi justru lebih kreatif.
Penelitian lain dalam Frontiers in Psychology berjudul “The Effect of Short-Form Video Addiction on Undergraduates’ Attentional Control and Academic Procrastination” oleh J. Xie, Y. Zhang, dan X. Zhang (2023) menemukan bahwa penggunaan berlebihan video pendek di media sosial menurunkan kemampuan kontrol perhatian dan meningkatkan kecenderungan menunda tugas akademik. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kali seseorang terbiasa dengan kecepatan informasi yang instan, otaknya kehilangan ketahanan untuk menikmati proses perlahan yang justru dibutuhkan ketika membaca.
Masalahnya bukan lagi sekadar “bosan membaca”, tetapi “terlalu cepat ingin selesai”. Video, gambar, dan suara telah memberi dopamin instan yang menipu: terasa memuaskan, padahal hanya menyentuh permukaan. Sementara teks justru menuntut kedalaman. Ketika kata “hijau” tertulis di halaman, setiap kepala bebas membayangkan warna dan suasana yang berbeda. Tidak ada dua “hijau” yang sama, sebagaimana tidak ada dua tafsir yang identik. Di situlah letak keajaiban membaca: ia memberi ruang bagi kebebasan imajinasi yang tidak dimiliki media visual.
Namun ketika imajinasi telah tumpul, membaca terasa berat. Buku kehilangan daya pesonanya, karena pembaca tidak lagi membangun dunia di kepalanya. Semua huruf terasa datar, seperti layar yang padam. Itulah sebabnya, latihan membaca yang baik sebenarnya adalah latihan menghidupkan imajinasi kembali. Caranya bisa sesederhana berhenti sejenak di tengah bacaan, lalu membayangkan adegan yang baru saja dibaca. Apa warna langitnya? Bagaimana suara langkah tokohnya? Apa aroma tempat itu? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini bukan sekadar permainan, tetapi cara mengaktifkan kembali pelenting imajinasi yang tertidur.
Salah satu penulis sastra yang sering disebut memiliki kemampuan memancing imajinasi pembaca adalah Haruki Murakami. Dalam novelnya Kafka on the Shore, adegan-adegan absurd tidak dijelaskan secara gamblang. Pembaca dibiarkan mengisi ruang kosong dengan tafsir pribadi. Murakami seolah percaya bahwa pembaca tidak harus paham seluruhnya, yang penting mereka ikut bermimpi. Inilah contoh bagaimana teks memberi ruang luas bagi pembaca untuk berpartisipasi. Membaca semacam itu tidak pernah membosankan, karena setiap kepala menciptakan dunianya sendiri.
Buku pengembangan diri yang baik pun bisa bekerja dengan prinsip serupa. The Artist’s Way karya Julia Cameron, misalnya, tidak memberi formula tunggal untuk menjadi kreatif. Ia justru mengajak pembaca berdialog dengan dirinya sendiri lewat latihan harian dan refleksi pribadi. Pembaca yang mengikuti ajakannya akan merasakan bahwa membaca bukan hanya menyerap nasihat, tapi juga berproses. Buku itu hidup karena ia menyentuh wilayah imajinasi dan pengalaman, bukan sekadar logika.
Pada akhirnya, agar tidak mudah bosan membaca, seseorang perlu berhenti menganggap buku sebagai guru yang harus diikuti. Buku adalah teman bicara. Ia bisa disangkal, disetujui, atau ditafsir ulang. Ketika membaca, pembaca perlu memberi respons, entah dengan mencatat, menandai, atau menulis ulang pemahamannya. Bahkan ketika isi buku terasa membosankan, selalu ada ruang untuk membuatnya relevan—dengan membawanya ke pengalaman sendiri, dengan membayangkan ulang dunia yang ditulisnya, atau dengan menantangnya secara kritis.
Mungkin ini saatnya berhenti menyalahkan buku atau penulis, dan mulai memulihkan imajinasi yang terluka oleh layar. Jika pelan-pelan kamu kembali membaca, bukannya malah scroll medsos atau menonton Netflix, kamu sedang menjalani proses penyembuhan. Tak ada pil yang manis untuk penyembuhan. Tak ada operasi tanpa melukai bagian tubuhmu. Kamu tak punya pilihan selain menjalaninya: tetap membaca. Bedanya, karena sedang recovery, kamu melakukannya pelan-pelan dan penuh kesadaran bahwa setiap kata adalah undangan untuk menyalakan kembali dunia yang lama padam di kepalamu—sebuah dunia yang, bila kau rawat terus dengan membaca, akan tumbuh menjadi semesta kecil yang hanya kamu yang tahu bentuknya. Ach, kalau sudah begini, mengutip Yusrizal KW, membaca adalah kesunyian yang paling keren!
Lubuklinggau, 31 Oktober 2025
2 Comments
Bisa bertahan baca satu buku itu buatk sendiri ada banyak variabelnya. Pengalaman hidup pembaca secara gak langsung juga akan berkorelasi dengan apa yang tengah dibaca. Menurutku begitu, sih.
Jadi reminder banget buat kita: jangan cuma konsumsi pasif, tapi ikut berpikir, bertanya, membangun dunia di kepala kita saat baca. Terima kasih banyak untuk insightnya, Bang Ben 😍👍🏻